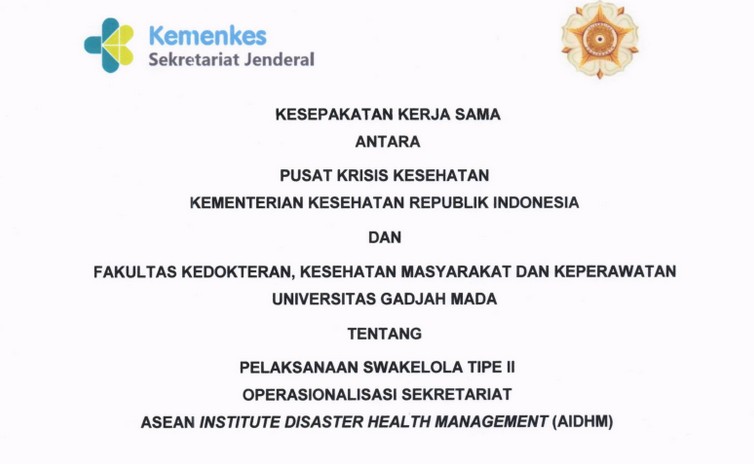Birokrasi Tanpa Dinding: Merajut Sinergi di Era WFA
Penulis: Yudianto, Pranata Komputer Ahli Madya di Biro Umum
Ringkasan
Di tengah derasnya arus transformasi digital, birokrasi kita berdiri di persimpangan keniscayaan: beradaptasi atau dilindas waktu. Fenomena Work From Anywhere membuka jendela ke dunia kerja tanpa batas—sebuah birokrasi tanpa dinding yang sekaligus mengungkap rapuhnya fondasi sosial yang selama ini menopangnya. Di sinilah paradoks mencuat: sejauh mana kita bisa adaptif dan fleksibel, tanpa kehilangan kohesi dan jiwa kolektif?
Seperti akar yang merambat ke dalam tanah, birokrasi masa kini menuntut fondasi yang bukan hanya fisik dan digital, tetapi juga infrastruktur sosial yang relasional—tempat empati, kolaborasi, dan komunikasi digital tumbuh sebagai simpul-simpul inheren dalam setiap interaksi. Di era ketika ruang kerja berpindah ke layar, komunikasi digital menjadi tulang punggung birokrasi modern—penentu arah, penguat gravitas relasi, serta penjaga work-life balance agar tak terkikis oleh digital fatigue.
Birokrasi kini adalah ekosistem yang ditenagai oleh modal sosial sebagai energi pengikat kolektif, melintasi batas peran dan ruang kerja. Dalam momentum perubahan ini, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, melainkan bahasa baru yang membangun jembatan pengertian—yang terhubung dengan nurani dan akal sehat. Work From Anywhere menuntut budaya birokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas, antara kebebasan bergerak dan arah bersama—dan semua itu ditopang oleh komunikasi digital yang inklusif, kohesif, dan bermakna.
Transformasi ini bersifat signifikan, bukan hanya karena menyentuh cara kerja, tetapi karena menuntut perubahan cara berpikir—dari yang mekanistik menjadi lebih humanis, dari yang kaku menjadi fleksibel, dari yang hirarkis menjadi lebih kolaboratif. Dalam dunia kerja yang semakin asimetris, konektivitas menjadi nilai strategis yang menentukan keberhasilan organisasi: bukan sekadar siapa yang bekerja di mana, tapi bagaimana semua tetap merasa terhubung dalam visi bersama.
Ini adalah perjalanan menuju birokrasi yang bukan hanya bertahan, tetapi berkembang—fleksibel namun kokoh, beragam namun utuh, serta mengisi ruang-ruang kosong dengan makna yang lahir dari empati, kesadaran, dan kualitas interaksi digital yang terjaga.
Artikel ini hadir sebagai undangan reflektif, untuk mengurai benang kusut birokrasi modern dan menyalakan kesadaran kolektif bahwa birokrasi bukan sekadar struktur, tetapi makhluk hidup dalam sistem sosial yang dinamis dan penuh paradoks. Ia harus mampu menari lincah di lanskap digital tanpa kehilangan akarnya—mengelola komunikasi digital sebagai alat perekat sosial, serta memelihara modal sosial sebagai kekuatan tak kasat mata namun penuh daya. Birokrasi masa depan adalah simfoni antara teknologi dan kemanusiaan—fungsional sekaligus futuristik, tempat setiap nada mewakili keberanian untuk berubah dan kekuatan untuk tetap terhubung.
Pengantar
“Di era kerja fleksibel, yang paling rentan bukanlah sistem pengawasan, melainkan komunikasi yang kehilangan makna.”
Kalimat ini bukan sekadar refleksi personal, tetapi realitas kolektif di tengah transisi besar birokrasi Indonesia menuju era kerja digital. Ketika interaksi tatap muka tergantikan oleh layar, dan notifikasi menggantikan kehadiran fisik, titik berat komunikasi digital dalam birokrasi pun bergeser—dari sekadar alat bantu koordinasi menjadi penopang utama kohesi dan budaya organisasi.
Transformasi ini diperkuat oleh lahirnya kebijakan Work From Anywhere (WFA) melalui Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2025, yang menginstitusikan fleksibilitas kerja sebagai norma baru. Namun perubahan ini tidak hanya bersifat teknologis atau prosedural. Yang lebih mendalam adalah perubahan dalam cara birokrasi membangun kepercayaan, membagi makna, dan merawat identitas kolektif di ruang kerja yang kini tersebar dan nyaris tak berbentuk.
Dalam konteks ini, work-life balance menjadi isu yang tak terhindarkan. Fleksibilitas kerja memang memberi otonomi, tetapi tanpa komunikasi digital yang cermat dan empatik, batas antara hidup pribadi dan kerja justru makin kabur. Ketidakhadiran fisik menuntut hadirnya relasi yang lebih manusiawi secara virtual—agar fleksibilitas tidak berubah menjadi beban tersembunyi.
Reformasi birokrasi telah memasuki babak baru—bukan lagi hanya tentang struktur, jabatan, atau prosedur, tetapi tentang bagaimana komunikasi digital dijadikan infrastruktur sosial. Di ruang virtual yang minim gestur dan basa-basi, komunikasi bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi menghubungkan, menyatukan, bahkan membangun rasa hadir di tengah ketidakhadiran fisik.
Artikel ini bertolak dari pemahaman tersebut: bahwa di tengah desentralisasi ruang kerja, birokrasi yang adaptif dan bermakna hanya mungkin lahir jika komunikasi digital diberi peran strategis—sebagai sarana, budaya, dan fondasi kepemimpinan yang juga memelihara work-life balance sebagai bagian dari keberlanjutan kerja.
Memaknai Birokrasi dalam Era Fleksibel
Transformasi kerja yang dipicu oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA) menuntut kita untuk meredefinisi ulang paradigma birokrasi. Tidak lagi cukup memaknai birokrasi sebagai sistem yang bergantung pada kehadiran fisik, hierarki formal, dan mekanisme pengawasan langsung. Di tengah fleksibilitas ruang dan waktu, birokrasi kini ditantang untuk membuktikan bahwa ia tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan terhubung—meski tanpa batas-batas ruang yang kaku.
Dalam konteks ini, penulis mengajukan tiga konsep kunci yang saling melengkapi dan menggambarkan orientasi baru birokrasi di era kerja fleksibel:
- Birokrasi Adaptif. Menggambarkan kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis—baik dalam hal regulasi, struktur organisasi, teknologi, maupun pola kerja. Birokrasi tidak lagi reaktif, tetapi proaktif dalam merespons dinamika dan kompleksitas zaman.
- Birokrasi Fleksibel. Menekankan pada pelonggaran struktur fisik dan prosedural, dengan fokus pada kinerja berbasis hasil (outcome-based), penggunaan teknologi sebagai pengungkit, serta otonomi pegawai sebagai modal kerja. Fleksibilitas bukan berarti kehilangan arah, tetapi memperluas ruang manuver untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien dan manusiawi.
- Birokrasi Tanpa Dinding. Merupakan metafora konseptual yang mencerminkan hilangnya batas ruang kerja konvensional. Interaksi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan kini berlangsung dalam ruang digital yang cair. Namun, dalam ketiadaan gedung fisik, kohesi dan akuntabilitas tetap harus terjaga melalui sistem kerja yang transparan, komunikasi yang bermakna, serta kepemimpinan yang menghubungkan.
Ketiga istilah ini bukan sekadar jargon, melainkan kerangka konseptual untuk memahami arah baru birokrasi: bukan sekadar soal tempat kerja, tetapi soal cara bekerja; bukan soal kehadiran fisik, tetapi soal kontribusi yang terukur; bukan soal kendali struktural, tetapi soal kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi dan tanggung jawab.
Birokrasi masa depan tidak ditentukan oleh keberadaan dalam satu gedung, tetapi oleh kemampuannya menjaga konektivitas, membangun makna bersama, dan tetap menghadirkan pelayanan publik yang prima dalam lanskap kerja yang tersebar.
Paradoks WFA: Fleksibilitas yang Menantang Kohesi
Secara teori, skema Work From Anywhere (WFA) menjanjikan banyak hal: jam kerja yang lebih lentur, efisiensi anggaran, fokus pada hasil kerja, serta keseimbangan hidup yang lebih baik (work-life balance) bagi Aparatur Sipil Negara.
"Fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis.”
— Nanik Murwati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan-RB [8]
ASN tidak lagi harus berjibaku melawan kemacetan atau menghabiskan waktu di ruang tunggu. Di atas kertas, semuanya terlihat ideal. Namun dalam praktik, fleksibilitas ini membawa dampak berlapis—dan sebagian tidak mudah dikenali.
Tapi seperti halnya setiap kebebasan, fleksibilitas juga datang bersama tanggung jawab baru—terutama dalam menjaga ikatan kolektif di ruang kerja yang makin abstrak.
Dalam birokrasi klasik ala Weber, kontrol dan kepatuhan dibentuk oleh struktur hierarkis, kedekatan fisik, dan prosedur yang rigid. Ketika ruang dan waktu menjadi cair seperti dalam skema WFA, kontrol tidak lagi bersandar pada kehadiran, melainkan pada kepercayaan, akuntabilitas digital, dan literasi teknologi. Ini menuntut bentuk kedisiplinan baru yang tidak selalu terdukung oleh kultur birokrasi konvensional.
Di sinilah letak paradoksnya: kendali atas waktu dan tempat kini berada di tangan individu,
tetapi organisasi justru menghadapi tantangan dalam menjaga kekompakan, semangat kolektif, dan kelancaran aliran informasi.
Beberapa gejala yang kini muncul sebagai konsekuensi dari sistem kerja yang tersebar ini antara lain:
- Erosi Interaksi Humanis. Percakapan ringan di lorong kantor atau obrolan santai saat makan siang bukan sekadar basa-basi. Ia adalah fondasi kepercayaan dan kolaborasi tim. Ketika momen itu hilang, relasi antar rekan kerja berisiko menjadi transaksional—terbatas pada tugas, tanpa ruang emosional. Menurut Putnam (2000), interaksi sosial informal adalah komponen vital yang membangun social capital, yang memperkuat kohesi dan kinerja organisasi [11].
- Zoom Fatigue dan Kejenuhan Virtual. Alih-alih menjadi solusi efisien, rapat daring yang berlangsung maraton justru menimbulkan kelelahan kognitif. Terlalu sering berpindah antara layar presentasi, wajah-wajah beku di grid kamera, dan suara yang putus-nyambung membuat komunikasi kehilangan kedalaman dan spontanitas. Studi Bailenson (2021) menyebut fenomena ini sebagai Zoom fatigue, yang berdampak signifikan pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja [2].
- Isolasi Organisasi dan Memudarnya Budaya Kerja. Ketika ASN bekerja dari titik-titik geografis yang berbeda tanpa sentuhan fisik, identitas organisasi berisiko merosot menjadi sekadar dokumen nilai. Budaya kerja yang sebelumnya terinternalisasi lewat teladan dan atmosfer kantor kini harus direka ulang dalam bentuk digital—sebuah tantangan tersendiri. Schein (2010) menekankan bahwa budaya organisasi terbentuk dari pengalaman kolektif dan interaksi sehari-hari, yang sulit digantikan oleh komunikasi digital semata [12].
- Asimetri Teknologi dan Ketimpangan Infrastruktur. Tidak semua ASN memiliki akses yang setara terhadap perangkat kerja dan koneksi internet. Perbedaan ini memengaruhi kecepatan, kualitas komunikasi, bahkan beban kerja. ASN di daerah yang kesulitan sinyal kerap terdiskoneksi—baik secara literal maupun struktural. Penelitian Az’zahra et al. (2024) menyoroti bagaimana disparitas infrastruktur digital dapat menjadi faktor penghambat utama efektivitas WFA di lingkungan pemerintahan Indonesia [1].
Empat gejala ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah lanskap baru relasi kerja — di mana struktur yang dulu kasat mata (seperti jam kerja, seragam, meja kantor) telah digantikan oleh struktur implisit seperti kepercayaan, intensi, dan pola komunikasi digital. Jika struktur lama memaksa keterikatan lewat kehadiran fisik, struktur baru menuntut kesadaran untuk hadir secara relasional — hadir bukan hanya secara daring, tetapi juga secara bermakna.
Fleksibilitas kerja memang memberikan ruang gerak yang luas. Namun tanpa penataan komunikasi yang matang, ia berisiko memperlebar jurang koordinasi. Di sinilah letak paradoks WFA: semakin longgar struktur fisiknya, semakin besar kebutuhan akan keterhubungan non-fisik yang kuat dan bermakna.
Di tengah kelonggaran struktur, justru kebutuhan akan keterhubungan emosional dan profesional semakin mendesak. WFA bisa menjadi loncatan transformasi—tapi hanya jika komunikasi difungsikan sebagai pengikat, bukan sekadar pengantar pesan. Untuk itu, WFA memerlukan penataan komunikasi yang bukan hanya fungsional, tetapi relasional. ASN butuh ruang kerja virtual yang tidak hanya mendukung kerja, tetapi juga menciptakan rasa hadir secara emosional.
Mungkin inilah tantangan terbesar dari birokrasi fleksibel: bukan sekadar mengelola kerja dari mana saja, tetapi membangun rasa kebersamaan meski berada di mana-mana.
Akuntabilitas Tanpa Tatap Muka: Masalah atau Momentum?
Ketidakhadiran fisik tak lagi bisa dijadikan indikator utama kinerja. Di era Work From Anywhere (WFA), yang penting bukan lagi di mana seseorang bekerja, tetapi kontribusi nyata yang dihasilkannya. Namun ketika pengawasan visual dan kehadiran fisik tak lagi menjadi andalan, akuntabilitas kerja ASN memasuki fase transisi yang tidak selalu mulus. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: bagaimana mengelola kinerja di dunia yang semakin tidak kasat mata?
Dalam birokrasi tradisional, kehadiran sering kali dijadikan proxy dari produktivitas. Jam masuk dan pulang dicatat, absensi dihitung, dan keberadaan di meja kerja menjadi simbol tanggung jawab. Tapi dalam lanskap kerja yang terdispersi seperti WFA, semua itu runtuh. Kini, birokrasi ditantang untuk mengalihkan fokus dari rutinitas menuju hasil; dari proses ke outcome.
Sebagaimana dirangkum oleh penulis:
“WFA bukan tentang bekerja dari mana saja, tapi bekerja dengan hasil yang dapat diverifikasi dari mana saja.”
Kalimat ini merangkum pergeseran mendasar dalam orientasi kerja pemerintahan: dari pengawasan fisik menuju pengelolaan berbasis kepercayaan dan bukti kinerja. Esensi akuntabilitas bukan lagi soal hadir di ruang kerja, melainkan kemampuan menunjukkan kontribusi yang terukur, transparan, dan berdampak — di mana pun lokasi bekerja.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua instansi siap bertransformasi ke paradigma ini. Masih banyak pimpinan dan sistem evaluasi yang terpaku pada kehadiran sebagai ukuran utama. Inilah salah satu ironi birokrasi modern: teknologi membuka jalan, tetapi budaya lama justru menahan langkahnya.
“Tidak ada pendekatan satu untuk semua. Instansi diberikan keleluasaan untuk menetapkan model fleksibilitas yang paling tepat, asalkan tetap berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.”
— Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan-RB [8]
Misalnya, Kementerian PUPR mengakui bahwa sebagian besar tugasnya bersifat teknis dan lapangan, sehingga pelaksanaan WFA menghadapi keterbatasan.
“Kalau untuk full WFA ya agak susah, karena pelayanan kami sangat teknis.”
— Argy, ASN Teknis Kementerian PUPR, Kompas.com, 19 Juni 2025 [9]
Artinya, penerapan WFA tidak bisa disamaratakan. Ia memerlukan pemetaan menyeluruh atas jenis pekerjaan, fungsi pelayanan, dan kesiapan digital. Setidaknya terdapat tiga kelompok besar yang dapat menjadi dasar bagi segmentasi kebijakan WFA:
- Tugas administratif dan konseptual, seperti analis kebijakan, pranata komputer, dan perencana program — umumnya cocok untuk WFA penuh karena berbasis dokumen dan mandiri.
- Tugas teknis-lapangan dan supervisi, seperti pengawas bangunan, auditor lapangan, atau manajer proyek — lebih tepat memakai model hybrid karena tetap membutuhkan kehadiran pada fase tertentu.
- Tugas pelayanan langsung, seperti guru, tenaga medis, atau petugas layanan perizinan — cenderung tidak cocok untuk WFA penuh karena menuntut interaksi tatap muka intensif.
Segmentasi ini menuntut pimpinan birokrasi untuk lebih presisi dalam menetapkan harapan, serta lebih objektif dalam mengevaluasi hasil kerja. Di sinilah kepemimpinan berbasis kepercayaan (trust-based leadership) menjadi kunci utama.
Kepemimpinan Berbasis Kepercayaan: Tantangan Mentalitas
Perubahan ini sejatinya bukan sekadar soal teknis atau kebijakan, tetapi juga soal pola pikir. Menggeser pendekatan dari micromanagement ke trust-based leadership adalah tantangan mentalitas yang tidak kecil—baik bagi pemimpin maupun pegawai.
ASN perlu memahami bahwa akuntabilitas bukan berarti diawasi, melainkan mampu membuktikan kinerja secara bertanggung jawab. Sebaliknya, pimpinan perlu mengembangkan kapasitas untuk memimpin tanpa kontrol visual—berbasis data, dialog, dan kejelasan tujuan.
Menurut OECD (2023), transisi menuju kerja fleksibel di sektor publik berisiko gagal jika tidak diiringi dengan reformasi budaya kerja secara menyeluruh. Salah satu aspek krusial adalah penguatan sistem manajemen kinerja digital yang mampu menjembatani kepercayaan dan transparansi secara simultan. OECD juga menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan fleksibel, akuntabilitas tidak lagi bertumpu pada mekanisme pengawasan langsung, melainkan pada sistem pelacakan kinerja yang cerdas, berbasis data, dan didukung oleh komunikasi terbuka [10].
Menata Ulang Evaluasi Kinerja dalam Skema WFA
Dalam konteks ini, sistem penilaian ASN harus berkembang. Bukan lagi sekadar mencatat aktivitas, tapi menilai capaian strategis dan nilai tambah pekerjaan. Sistem seperti e-Kinerja perlu diperkuat agar benar-benar mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan outcome-based management.
“Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.”
— Nanik Murwati, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan-RB [8]
Beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh meliputi:
- Reformulasi indikator kinerja. Tidak semua pekerjaan bisa diukur secara kuantitatif; indikator naratif berbasis refleksi dan evaluasi menjadi penting.
- Integrasi dashboard monitoring real-time. Pengawasan bergeser dari inspeksi ke transparansi progres digital yang dapat dipantau bersama.
- Audit berbasis hasil, bukan rutinitas. Penghargaan diberikan pada dampak kerja, bukan pada durasi kehadiran atau banyaknya laporan.
Dengan pendekatan ini, WFA tidak hanya menjadi solusi darurat atau tren sesaat, tetapi juga momentum untuk membangun birokrasi yang lebih strategis, otonom, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Merancang Kerangka Kerja WFA yang Tangguh
Agar WFA menjadi sistem yang berdaya guna dan berkelanjutan, instansi perlu menyusun kerangka operasional yang adaptif namun terstandar. Setidaknya, lima komponen berikut dapat menjadi pilar:
- Pemetaan Jenis Tugas. Mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan kebutuhan kehadiran fisik, intensitas interaksi lintas fungsi, dan ketergantungan digital.
- Penetapan Kriteria WFA. Mencakup kesiapan individu, kesiapan teknis, dan klasifikasi pekerjaan sebagai dasar persetujuan model kerja fleksibel.
- Perencanaan Kinerja Fleksibel. Setiap ASN menyusun flexible work plan yang memuat target, indikator, dan waktu pelaporan secara digital.
- Monitoring Kinerja Digital. Dashboard e-Kinerja diperkuat untuk memantau output secara real-time dan akuntabel.
- Evaluasi dan Refleksi Berkala. Sesi evaluasi reguler dilakukan untuk menyesuaikan strategi kerja, mengatasi kendala, dan menjaga moral kerja.
Dengan sistem ini, fleksibilitas tidak menjadi alasan melemahnya akuntabilitas, tetapi justru menjadi sarana menguatkan profesionalisme, transparansi, dan tata kelola kerja modern.
Setelah membahas fondasi dan perubahan pola pikir yang diperlukan dalam birokrasi digital, kita akan menyelami lebih dalam aspek-aspek krusial yang membentuk birokrasi modern yang adaptif dan responsif. Bagian kedua ini akan mengulas bagaimana komunikasi digital bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan senjata strategis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Kita akan melihat bagaimana platform kolaborasi terintegrasi, protokol komunikasi yang jelas, serta literasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tulang punggung keberhasilan. Tak hanya itu, bagian ini juga akan menyoroti pentingnya menjaga koneksi emosional dalam ruang virtual demi mempertahankan semangat kebersamaan dan produktivitas.
Selanjutnya, kita akan beralih pada peran vital seorang pemimpin di era birokrasi tanpa dinding. Konsep "pemimpin fleksibel" akan dibedah, menyoroti pergeseran dari micromanagement menjadi outcome-based leadership. Pemimpin kini diharapkan menjadi digital orchestrator yang mampu menggerakkan tim secara efisien dalam ekosistem digital. Aspek empati juga akan dibahas sebagai strategi kepemimpinan yang esensial, bukan sekadar sentimen. Bagian ini akan ditutup dengan kesimpulan bahwa pemimpin masa depan adalah pengarah dan transformator, bukan lagi sekadar pengawas. Akhirnya, kita akan merangkum visi birokrasi tanpa dinding sebagai jalan menuju pemerintahan masa depan sebelum masuk ke bagian penutup.
Referensi
[1] Az’zahra, N. D., Anggodo, S. M., & Salvina, Z. (2024). Analisis Dampak Fleksibilitas Work From Anywhere (WFA) Terhadap Kinerja ASN. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(5), 427–436. Diakses dari https://doi.org/10.572349/neraca.v2i5.1530
atau https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1530
[2] Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1). Diakses dari https://doi.org/10.1037/tmb0000030
[3] Faizur, M., Khoiriani, A., & Susianti, S. (2023). Pengaruh penerapan skema Work From Anywhere (WFA) di Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. E‑Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 12(1), 1–8. Diakses dari https://doi.org/10.22437/pdpd.v12i1.27939 atau https://mail.online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/download/27939/18600/106828
[4] Harvard Business Review. (2025). Trust is the new control mechanism in remote teams. Harvard Business Publishing, edisi Februari 2025.
[5] Kementerian PANRB. (25 Januari 2023). Menteri Anas Dorong Penguatan 'Digital Leadership' pada Closing Ceremony ASN Culture Fest. Diakses dari https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-anas-dorong-penguatan-digital-leadership-pada-closing-ceremony-asn-culture-fest
[6] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/317321/permen-panrb-no-4-tahun-2025
[7] Kloepfer, S., & Carbon, C.-C. (2025). Leadership plays an important role in the functioning of remote teams, including creating conditions that can help build trust. Journal of Applied Psychology.
[8] Kompas.com. (18 Juni 2025). Aturan Baru, ASN Kini Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/06/18/18362931/aturan-baru-asn-kini-boleh-wfa-dan-jam-kerja-fleksibel
[9] Kompas.com. (19 Juni 2025). Ada Kebijakan Boleh WFA, ASN: Bisa Bikin "Work-Life Balance". Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2025/06/19/13130941/ada-kebijakan-boleh-wfa-asn-bisa-bikin-work-life-balance
[10] OECD. (2023). Government at a Glance 2023. OECD Publishing. Diakses dari https://doi.org/10.1787/9301f5b4-en
[11] Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Touchstone Books/Simon & Schuster. Diakses dari https://doi.org/10.1145/358916.361990
[12] Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). Jossey-Bass.